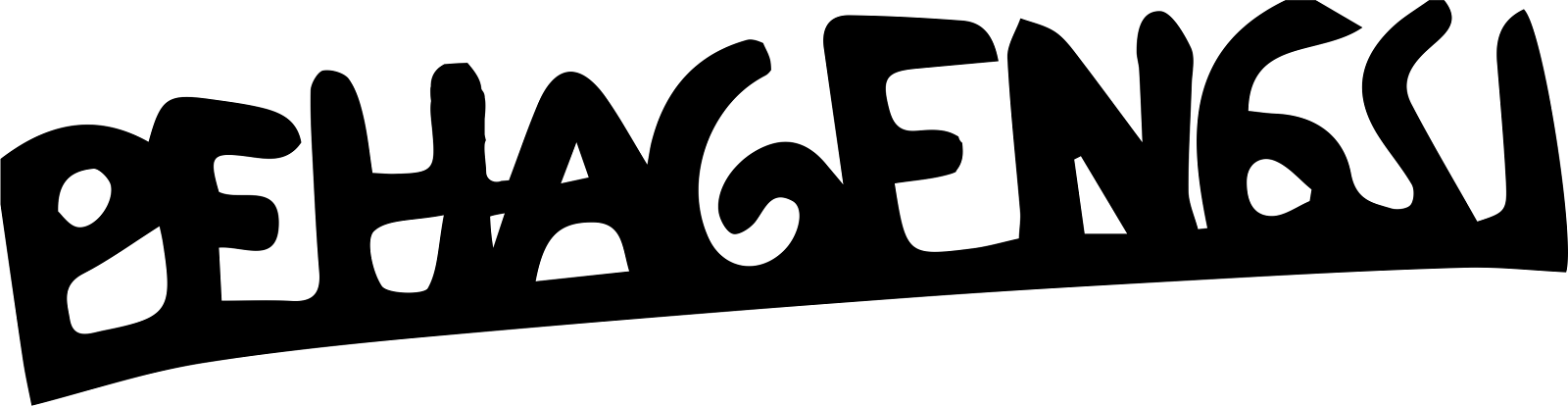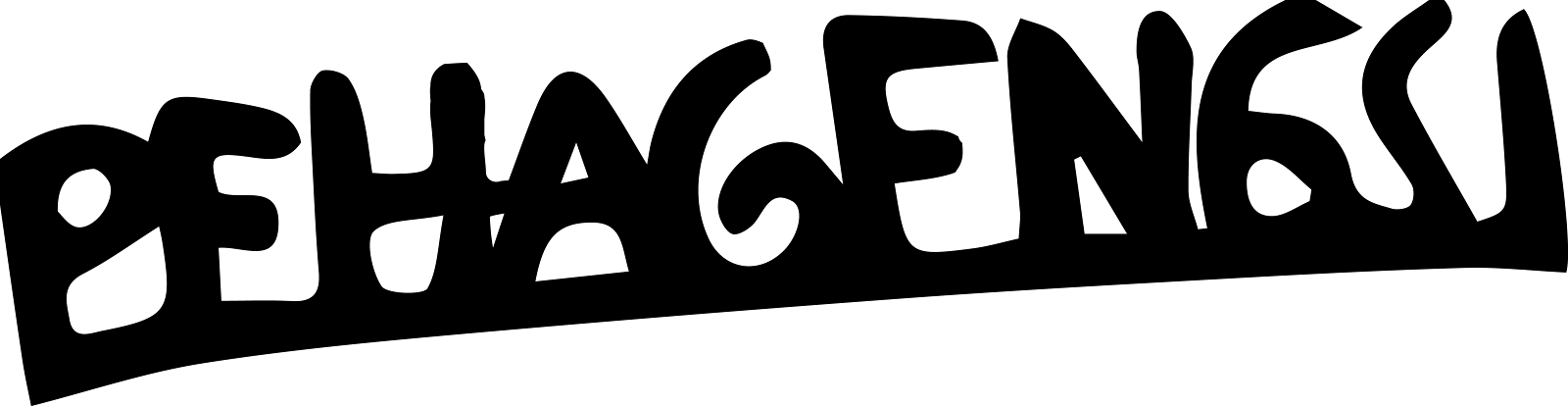Sebab Perfileman Jogja Layu Sebelum Berkembang
Gengs..gengs..
Emanuelle Levinas pernah bilang, waktu adalah sesuatu yang tak terbatas sekaligus melampaui ketidakmungkinan. Apa yang dibilang filosof yang memadukan tradisi agama, filsafat barat dengan pendekatan fenomenologis itu benar-benar mewujud di Jogja. Sebab, waktu adalah senjata rahasia Jogja yang enggak dipunyai kota lain, terlebih Jakarta. Banyak yang bilang, di Jakarta waktu terbuang di jalan sementara di Jogja, waktu terbuang di warung kopi.
Membincang hubungan Jakarta dan Jogja dalam dunia perfileman tampaknya harus bicara soal posisi dua kota itu dalam relasi sosial lebih dulu deh.
Bagaimana sesaknya Jakarta bisa dilacak dalam penelitian Alwi Shahab yang menuliskannya dalam Robinhood Betawi: Kisah Betawi Tempo Doeloe. Saat masa pemerintahan Coen, dari 1619-1623 penduduk Batavia mencapai 50.000 jiwa. Separuh penduduk adalah para budak yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Seiring waktu Batavia berkembang pesat menjadi kota dagang dan industri. Munculnya kantor-kantor besar dan pabrik mendorong orang desa mengadu nasib ke Batavia.
Streotipe Batavia sebagai 'tanah yang dijanjikan' dipertebal ketika Jogja mengembalikan ibu kota ke sana tahun 6 Juli 1949. Wacana nasionalisme dan kenegaraaan yang menggaung usai Agresi Militer makin menarik minat orang-orang dari luar untuk ke Jakarta.
Di sana mereka tergopoh-gopoh mengejar harapan dan janji-janji kemakmuran. Waktu punya nilai, terbatas, dan punya harga. Tahun 70an-dalam sebuah wawancara di majalah Prisma edisi Mei 1977-Gubernur Soemarno tahun 1962 bikin kebijakan non populis. Ia mengumumkan Jakarta sebagai kota tertutup. Setiap RT dan RW wajib melaporkan pendatang baru. Bagi mereka yang tak punya pekerjaan dilarang masuk Jakarta.
Namun, kebijakan itu gagal total. Jakarta tetap jadi tujuan orang-orang yang mencari kelahiran kedua. Pepatah waktu adalah uang menemukan bentuk terbaiknya.
Jogja sebaliknya, keseloan demi keseloan selalu melahirkan banyak hal yang menyenangkan sekaligus penting. Memang di tahun 70an Yogyakarta sempat jadi tujuan urbanisasi. Namun para kaum urban ini, merujuk pada penelitian Tadjuddin Noer Effendi yang dituliskan di Kompas tahun 1987 bisa bertahan hidup dengan bersiasat. Artinya tiap gerakkan mereka lahir setelah melewati obrolan panjang di pinggir jalan dengan warga sekitar atau dengan kelompok mereka sendiri.
Bagaimana Jogja bisa membuat mereka bertahan hidup dengan ngobrol saja itu ajaib banget. Di dunia perfileman juga. Kultur selo dan ngobrol itu melahirkan banyak gerakkan dan sineas edan yang berpengaruh—bahkan menjadi kronik—di perfileman Indonesia. Padahal Jogja nggak punya sekolah atau kampus film.
Bisa bebas nonton lalu bikin film saja baru setelah Orba runtuh (Baca: Gegar Film Post-Departemen Penerangan). Dibanding Jakarta yang sudah akrab dengan perfileman didukung fasilitas dan pendidikan, plus pengetahuan bisnis rasanya butuh waktu panjang untuk mengejarnya.
Namun ketidakmungkinan itu dibabat anak-anak Jogja lewat ribuan diskusi yang diselipi pertengaran, rasan-rasan, dan sekian percobaan yang mengejutkan dunia perfileman. Ditutupnya tirai pengetahuan karena mengedepankan aspek bisnis melahap Jakarta. Ide-ide perfilman kering. Talenta pun menukik.
"Sekarang apa yang dibawa Jakarta ke Jogja? Dalam perspektif politik, ya hanya uang. Uang! Jogja selo nggak punya uang tapi ilmune tinggi, Jakarta punya uang tapi nggak punya waktu. Terus sumbangsih Jogja ke industri (Jakarta) apa? Talent. Nuwun sewu, sutradara mana—yang apik banget—sekarang ini yang nggak ada hubungannya sama Jogja? Mana yang bisa dipisahkan sama Jogja?”
Gengs..
Yakin deh, dunia kreatif itu adalah medan pertempuran kuasa. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan yang bentuknya otoritatif. Pengetahuan lama-lama hanya memberi pilihan yang sifatnya ontologis: baik-benar, hitam-putih, dengan kata lain pragmatis. Jogja yang punya talen dan keseloan lama-lama ditelan Jakarta yang punya uang. Independensi yang dibesarkan keseloan tak lagi penting, bahkan cenderung ditanggalkan. Sebagian sineas sibuk dengan institusinya masing-masing, mulai jarang yang memikirkan Jogja.
“Pada akhirnya perfileman Jogja itu layu sebelum berkembang karena serakah. Talenta ditelan uang, masalah. Terus terang aku ragu, benarkah kita melakukan semua ini karena Jogja? Karena ilmu? Karena penting? Atau jangan-jangan kita semua menjadi independen karena gagal mainstream, pas dapat uang independensinya habis,” kritik Basbeth.
 Reviewed by pehagengsi
on
February 15, 2022
Rating: 5
Reviewed by pehagengsi
on
February 15, 2022
Rating: 5